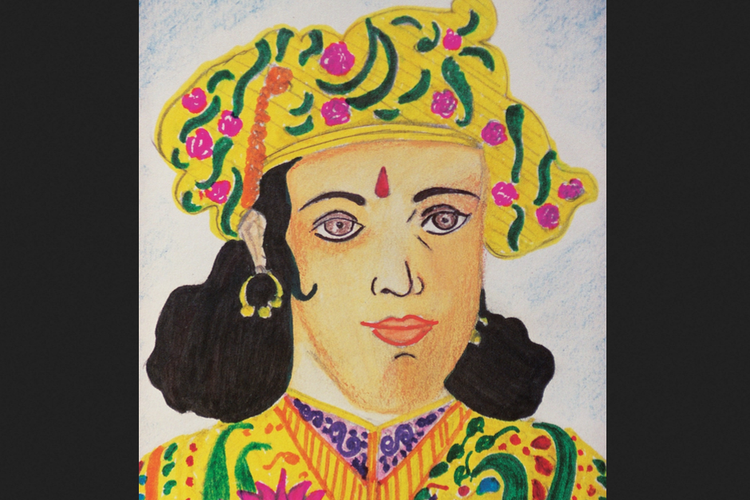Pernahkah agan mendengar "pertapaan"? Atau yang dalam istilah antropologi disebut "asketik"? Biasanya kata "asketik" sering disamakan dengan bermeditasi. Dan ketika mendengar kata "meditasi", maka yang selalu dalam bayangan kita pada umumnya adalah sikap duduk berdiam diri untuk merenung, yang biasanya berhubungan dengan spiritual dan supranatural. Atau ada juga yang membayangkan pertapaan sebagai sebuah aktifitas meninggalkan kehidupan duniawi untuk sepenuhnya hidup selibat. Apapun definisinya tentu tidak salah, akan tetapi sebenarnya pertapaan itu bermakna lebih luas. Jika mengacu pada KBBI: "tapa", bertapa adalah "mengasingkan diri dari keramaian dunia dengan menahan hawa nafsu (makan, minum, tidur, birahi) untuk mencari ketenangan batin", sehingga pertapaan adalah segala sesuatu mengenai kegiatan mengasingkan diri dari keramaian dunia dengan menahan hawa nafsu. Tentu saja, kita tidak akan puas dengan definisi ini. Namun, definisi ini menggambarkan karakter umum dari pertapaan baik dalam tradisi keagamaan maupun tradisi lainnya. Definisi yang lebih baik ditemukan dalam Encyclopedia Britannica: "asceticism", bahwa asketisme adalah "the practice of the denial of physical or psychological desires in order to attain a spiritual ideal or goal". Sampai sini, kita menemukan setidaknya pertapaan harus memenuhi kriteria: (1) mengabaikan hawa nafsu, (2) untuk tujuan spiritual tertentu. Karena memiliki suatu tujuan spiritual, maka pertapaan/asketisme seringkali diidentikkan dengan mistisisme. Dalam KBBI: "mistik", mistik adalah "subsistem yang ada dalam hampir semua agama dan sistem religi untuk memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan; tasawuf; suluk". Makna KBBI juga dirasa belum memenuhi kriteria mistik. Sementara itu, Encyclopedia Britannica: "mysticism" juga mencatat bahwa mistisisme adalah "the practice of religious ecstasies (religious experiences during alternate states of consciousness), together with whatever ideologies, ethics, rites, myths, legends, and magic may be related to them". Sejauh ini, definisi umum terbaik dari mistik adalah setidaknya memuat (1) sistem kepercayaan yang berhubungan dengan sesuatu yang adikodrati/beyond physics misalnya Tuhan, dewa, roh, malaikat, atau entitas gaib lainnya, (2) ekstase/pengalaman subyektif yang berkenaan dengan sistem kepercayaan tsb, dan (3) pemuasan hasrat manusia terhadap pengalaman dengan sesuatu yang adikodrati tsb.
Sampai sini kita menemukan makna yang perlu disepakati, bahwa asketisme adalah suatu kebiasaan, atau perilaku, yang biasanya berupa aktifitas mengabaikan hawa nafsu untuk mencapai suatu tujuan spiritual, yang dalam perjalanannya, asketisme membuahkan mistisisme. Sedangkan mistisisme adalah suatu gagasan yang berkenaan dengan suatu kepercayaan dan supranatural yang diperoleh dari suatu pengalaman spiritual, yang di antaranya melalui pertapaan. Dengan definisi ini, maka kita dapat membedakan antara bertapa dengan sekedar berpikir dan merenung. Namun, yang jadi pertanyaan selanjutnya, sejak kapan manusia bertapa? Dan apa yang dihasilkan dari pertapaan?
Sepanjang sejarah peradaban manusia, terdapat sebuah gerakan yang disebut sebagai Śramaṇa yang populer di India abad ke-4 SM. Meskipun jarang sekali dari kita mendengar gerakan Śramaṇa ini, namun peranannya sangat penting terutama dalam kaitannya dengan kemunculan tradisi pertapaan. TS telah merangkum secara runut mulai dari latar belakang Śramaṇa sampai pengaruhnya di kemudian hari.
BACA JUGA :
Latar Belakang

Manusia merenung tentang arti/kehidupan sudah dimulai sejak sistem bahasa pertama kali diciptakan. Pertanyaan-pertanyaan filosofi tentang kenapa alam semesta bisa ada, untuk apa manusia ada, apakah ini semua ada tujuannya, dsbnya adalah pertanyaan-pertanyaan dasar sebagai efek dari kemampuan berbahasa yang pada akhirnya mengembangkan kepercayaan-kepercayaan yang berkaitan dengan sesuatu yang melampaui fisis (beyond physics). Kepercayaan-kepercayaan ini lahir sebagai jawaban sementara agar, setidaknya, manusia dapat menghentikan rasa ingin tahunya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak/belum dapat dijangkau oleh pengetahuan dan teknologi saat itu. Kepercayaan-kepercayaan ini telah memberikan nilai spiritual/semangat untuk manusia dalam menjalani kehidupannya, yang berkaitan dengan insting bertahan hidup (survival). Dengan adanya kepercayaan-kepercayaan ini, manusia dapat kembali fokus mengembangkan sistem teknologi mereka untuk menjadi alat bertahan hidup. Tidak dimana-mana, termasuk di India.
Di India circa pada abad ke-20 SM, lebih tepatnya di sebuah lembah sungai Indus, manusia telah mulai membangun kehidupannya dengan sangat maju. Tidak hanya sistem hirarki kemasyarakatan, tapi juga kearifan lokal telah membentuk identitas Peradaban Lembah Indus. Di sini, kesengsaraan (saṃsāra) dan pembebasan diri dari kesengsaraan (mokṣa) menjadi tema utama yang dibahas oleh masyarakat. Mereka percaya bahwa, pada dasarnya, di alam semesta ini hanya ada 1 (satu) realitas yang disebut Brahman. Realitas ini memancarkan kesadarannya menjadi bagian-bagian kecil, yang disebut Ātman. Ātman kemudian merasuk ke dalam realitas semu yang disebut sebagai jiva yang membentuk jati-diri makhluk hidup, termasuk manusia. Di saat itulah, kesengsaraan dimulai. Kehidupan nyata dipandang sebagai suatu kesengsaraan yang merupakan akibat / "buah pembalasan" (karmapala) dari jiva tidak menyadari keberadaan Ātman. Semakin banyak kesalahan (doṣa), maka manusia akan semakin sulit untuk melepaskan diri dari kesengsaraan, atau bahkan bisa membawa kesengsaraan baru melalui reinkarnasi ke dalam wujud makhluk yang lebih buruk. Oleh sebab itu, muncul trend orang-orang berlomba-lomba untuk berteguh dalam berbuat kebajikan. Dari antara orang-orang itu, muncul pula orang-orang yang dipercaya telah memperoleh pencerahan/pengetahuan sejati tentang cara meraih pembebasan dari kesengsaraan (mokṣa), dan mereka disebut sebagai Rśi. Para Rśi tidak hanya mengajarkan moralitas saja, namun juga ritual untuk mencapai mokṣa melalui puja dan mantra. Dari merekalah, tradisi periwayatan Samhita muncul, meskipun teksnya bisa jadi muncul belakangan. Samhita merupakan koleksi mantra yang diciptakan dan diajarkan para Rśi, yang di kemudian hari tergabung dalam bagian pertama kitab Rigveda.

Lembah sungai Sindhu (Indus)
Para Rśi mengajarkan mantra dan puja kepada banyak orang. Sampai sini, muncullah kelompok yang disebut sebagai Āstika. Mereka yang menjadi murid-murid para Rśi kemudian menjadi orang-orang yang secara khusus mencurahkan hidupnya untuk kemudian hari membimbing dan membina spiritual masyarakat awam, dan kemudian tergabung dalam kasta Brahmaṇa. Mereka yang disebut Brahmaṇa adalah orang-orang yang secara khusus memiliki pengetahuan ajaran para Rśi dan mengajarkannya kepada orang-orang awam. Para Brahmaṇa terdiri dari:
- Pandita ("pelayan/pendeta"), yang bertugas memberikan pelayanan ritual yang teknis kepada masyarakat. Biasanya keluarga mereka secara turun-temurun mengelola mandir (candi/pura) yang disebut sebagai Purahita.
- Guru ("pembina"), yang bertugas mengajarkan pengetahuan tekstual (agama) kepada khususnya para santri calon pandita. Mereka umumnya telah bergelar acharya ("pembimbing").
Para Brahmaṇa pada umumnya terbiasa melantunkan mantra. Di kemudian hari, koleksi mantra dan komentar dari para Brahmaṇa dikompilasikan ke dalam teks Rigveda sekaligus menandakan dimulainya Periode Vedis (Vedic Period) circa 1500-500 SM.
Para Brahmaṇa dipercaya memiliki pengetahuan eksklusif dan mendalam terhadap Veda, dan mengajarkan pengetahuan tsb kepada masyarakat umum. Para Brahmaṇa juga memiliki keahlian khusus pada masa itu, yaitu membaca, menulis, dan menghapal. Merekalah yang dipercaya memahami teks-teks berbahasa Sansekerta Kuno (Archaic Sanskrit / Vedic Sanskrit) dan mereka jugalah yang konon menghimpun dan menulis Literatur Veda. Kegiatan penulisan literatur Veda ini berjalan secara bertahap selama berabad-abad dari abad ke-15 s.d. 5 SM. Akan tetapi, meskipun literatur Veda sudah ditulis, bukan berarti Veda mudah dibaca, apalagi didapatkan. Distribusi pengetahuan Veda tidak utuh dan tidak merata kepada kalangan umum orang-orang India kuno. Selain disebabkan karena sulitnya memperoleh material tulisan dan rendahnya kemampuan baca-tulis di masa itu, juga karena memahami Veda membutuhkan kemampuan hapalan. Akibatnya, pengetahuan Veda merupakan pengetahuan yang eksklusif hanya dimiliki kasta Brahmaṇa pada Periode Vedis itu.
Pada periode itu pula, pertanyaan-pertanyaan filosofis dipertanyakan kembali oleh sebagian orang non-Brahmaṇa. Tema saṃsāra dan mokṣa kembali ditanyakan, yang kali ini lebih serius dan kritis. Pertanyaan seperti: apa penyebab kesengsaraan, apakah peribadatan Vedis sudah dapat membebaskan diri dari kesengsaraan, apakah kesengsaraan itu realita, apa itu realita, apa yang sebenarnya benar secara sejati, dll adalah pertanyaan-pertanyaan yang tadinya hanya dibahas dalam lingkungan Brahmaṇa, dan kali ini dibahas secara luas dan menimbulkan daya tarik bagi masyarakat India secara umum. Bagi sebagian orang lainnya, mereka merasa sudah mendapatkan jawabannya dari para Brāhmaṇa. Namun, ada sebagian lainnya yang merasa tidak memperoleh jawaban. Biasanya mereka tidak puas dengan jawaban yang disajikan para Brahmaṇa. Karena muncul rasa ketidakpuasan itulah, maka banyak orang dari kasta non-Brāhmaṇa (biasanya dari kasta Kṣatriya dan Vaiṣa) mencoba mencari jawaban sendiri dengan usaha sendiri secara bebas. Mereka yang mencoba melepaskan secara penuh tradisi Veda dan mengembangkan filsafatnya sendiri inilah yang kemudian dikenal sebagai Nāstika.
Dalam rangka mengembangkan filsafatnya sendiri, mereka yang tergolong Nāstika biasanya akan memulainya dengan mengembara kemana saja, meninggalkan kampung halaman atau tanah kelahiran untuk bertemu dengan orang-orang berilmu di daerah lain, bertanya, dan bahkan berguru dengan orang-orang baru. Dan di antara mereka yang tidak puas dengan jawaban atau pengetahuan yang mereka peroleh, mereka akan mencoba mencari jawaban dengan cara: (1) mengamati alam sekitar, dan (2) merenung. Namun, merenung di sini bukanlah sekedar berpikir. Mereka yang memiliki penghayatan falsafi yang sangat mendalam biasanya berpendapat bahwa kegiatan berpikir itu bias, terbiaskan oleh keyakinan diri sendiri, atau oleh pencerapan inderawi, atau bahkan kegagalan dalam berlogika. Akhirnya, mereka mencoba mengembangkan metode untuk berkonsentrasi seluas-luasnya. Ada yang mencoba belajar berkonsentrasi dengan cara duduk menatap lilin, atau duduk di bawah tekanan air terjun, berdiri di tengah sungai yang mengalir deras, sambil melantunkan berbagai irama (mantra), atau bahkan lebih ekstrim lagi.... bergelantungan secara terbalik di atas pohon seperti kelelawar. Semua kegiatan mencari jawaban filosofis ini, mulai dari mengembara, bertanya dengan orang-orang baru, berguru dengan orang-orang lain, berkeliling hutan mengamati alam, hingga merenung dan mencoba berkonsentrasi, adalah kegiatan yang bisa disebut pertapaan paling dasar. Selama abad ke-15 s.d. 9 SM, para pertapa Nāstika saling berbagi informasi, bertukar pengetahuan, bertukar metode, membangun perguruan kecil sendiri, mengajarkan ke orang lain, dstnya. Para pertapa Nāstika ini yang di kemudian hari dikenal sebagai Śramaṇa.
BACA JUGA :
Nāstika dan Śramaṇa Awal (1)

Sebenarnya, istilah Śramaṇa adalah sebuah istilah yang disematkan oleh teks-teks kanon Buddhisme (Kanon Pali) terhadap sekelompok orang yang terbiasa bertapa mengembara melanglang-buana. Kata ini dari bahasa Pali yang artinya "para pencari", yang merujuk pada orang-orang yang mengerahkan seluruh daya yang dimilikinya untuk mencari dan mencapai pencerahan/pengetahuan sejati. Namun, dalam perspektif historis, kata Śramaṇa lebih erat kaitannya dengan sebuah trend pertapaan yang dilakukan oleh orang-orang non-Brahmaṇa, dimana sebelumnya pertapaan tidak pernah dilakukan oleh selain kasta Brāhmaṇa.
Pada masa awal Periode Vedis, setidaknya muncul 2 (dua) kelompok aliran filsafat, yaitu Āstika dan Nāstika sebagaimana telah dibahas di atas. Dalam tradisi Hinduisme, kelompok Āstika adalah kelompok yang mempercayai keberadaan Brahman ("Jiwa Tunggal Adikodrati" yang bersifat transenden, atau di dalam Hindu Bali disebut "Sang Hyang Widhi Wasa Maha Esa" atau Acintya), sedangkan kelompok Nāstika adalah kelompok yang menolak keberadaan Brahman. Kedua kelompok ini sering terlibat dalam diskusi dan perdebatan. Mereka membangun tradisi dialektika yang sangat polemikal, sehingga kata Śramaṇa seringkali dimaknai sebagai secara peyoratif. Misalnya, bagi kelompok Āstika, Śramaṇa adalah sebutan untuk kelompok Nāstika. Sementara bagi kelompok Nāstika, Śramaṇa adalah sebutan untuk kelompok Āstika. Selain itu, tidak semua kelompok Nāstika menolak konsep Brahman. Sebagian dari mereka ada yang mempercayai keberadaan sesuatu yang adikodrati, hanya saja mereka menolak apa yang diajarkan oleh Veda. Oleh sebab itu, kita dapat memberikan definisi yang lebih fair terhadap keduanya sbb:
- Āstika adalah kelompok yang memegang teguh tradisi dan doktrin Veda dengan ketat, yang kemudian bertransformasi menjadi Hindu orthodoks.
- Nāstika adalah kelompok yang menolak tradisi dan doktrin Veda, sehingga dapat disebut Hindu heterodoks.
Menjelang abad ke-6 SM, kelompok Nāstika menjadi beragam aliran pemikiran, dan di saat itulah sebutan Śramaṇa lebih sering digunakan untuk kelompok Nāstika.
Beberapa mazhab/sekolah filsafat Āstika yang telah berdiri di abad ke-6 SM adalah:
- Nyāya (न्याय), sebuah aliran Hindu orthodoks yang mempercayai bahwa pengetahuan sejati diperoleh melalui metode kombinasi antara: (1) penalaran melalui pencerapan/persepsi (pratyakṣa); (2) penalaran melalui praduga/hipotesis (anumāṇa); dan (3) penalaran melalui penukilan petuah/kuotasi (śabda). Mereka disebut juga sebagai mazhab idealisme dalam Hindu orthodoks.
- Vaiśeṣika (वैशेषिक), sebuah aliran Hindu orthodoks yang mempercayai bahwa pengetahuan sejati diperoleh melalui metode kombinasi antara: (1) pratyakṣa; (2) anumāṇa; (3) penalaran melalui perbandingan/analogi (upamāna); (4) penalaran melalui pemikiran/kognisi (anupalabdhi); (5) penentuan batasan-batasan mutlak/postulasi (arthāpatti); dan (6) śabda. Mereka disebut juga sebagai mazhab naturalisme dalam Hindu orthodoks.
- Sāṃkhya (साङ्ख्य), sebuah aliran Hindu orthodoks yang mempercayai bahwa pengetahuan sejati diperoleh melalui 2 (dua) pengalaman mutlak: (1) pengalaman berpikir sadar (buddhi puruṣa); dan (2) pengalaman berpikir teratur/budi pekerti (buddhi prakṛti). Mereka disebut juga sebagai mazhab dualisme dalam Hindu orthodoks.
- Yoga (योग), sebuah aliran Hindu orthodoks yang mempercayai bahwa pengetahuan sejati diperoleh melalui fokus penuh ke dalam diri sendiri/konsentrasi (samādhi). Mereka disebut juga mazhab praktis dalam Hindu orthodoks.
- Mīmāṃsā (मीमसा), sebuah aliran Hindu orthodoks yang mempercayai bahwa pengetahuan sejati diperoleh dari hermeneutika teks-teks Veda, utamanya teks-teks paling awal (pūrva charākā). Mereka disebut juga mazhab tekstualisme dalam Hindu orthodoks. Di dalam Mīmāṃsā, juga terdapat sub-sekte: (1) Karma-Mīmāṃsā, yang berfokus pada hubungan perilaku dengan teks; dan (2) Uttara-Mīmāṃsā / Vedānta, yang berfokus pada teks.
Diskusi filsafat bagi kalangan Āstika hanya dilakukan dalam lingkungan akademik yang terbatas dengan kemampuan intelektual yang juga terbatas, yaitu hanya pada kasta Brāhmaṇa. Biasanya, masyarakat awam tidak memiliki kemampuan intelektual yang cukup untuk membahas filsafat.
Berbeda dengan Nāstika yang sangat luas dan jauh lebih beragam daripada Āstika. Kalangan Nāstika cenderung inklusif (terbuka) terhadap diskusi-diskusi filsafat, yang biasanya disebabkan ketidakpuasan sejumlah orang dari kasta Kṣatriya dan Vaiṣa. Sebagaimana telah dibahas pada bab Latar Belakang, beberapa di antara orang dari kasta Kṣatriya dan Vaiṣa berusaha untuk mencari sendiri jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar saṃsāra dan mokṣa, atau bahkan pertanyaan filosofis yang jauh lebih luas. Beberapa orang tsb kemudian mengembara dan memulai hidup selibat untuk memperoleh pengetahuan sejati. Di antara mereka tentu ada yang pada akhirnya berhasil "menemukan" pengetahuan sejati yang mereka cari dan mengundang rasa penasaran bagi masyarakat sekitarnya. Dari sinilah mereka memberikan nasehat dan pelajaran, bahkan juga perguruan yang akhirnya menjadi mazhab-mazhab Nāstika. Dari sanalah istilah Śramaṇa mulai digunakan dan disematkan kepada mereka.
Hanya saja, kita tidak memiliki catatan sejarah yang cukup mengenai apa saja mazhab/sekolah/aliran pemikiran Nāstika yang beredar sebelum abad ke-5 SM. Setidaknya, kita hanya menemukan atestasi dari tradisi Buddhisme tentang 6 (enam) orang tokoh pertapa Nāstika/Śramaṇa yang hidup relatif sezaman, atau lebih tua sedikit, dengan Siddhartha Gautama / "Sang Buddha" (w. circa 483/400 SM).
Yang pertama adalah Purana Kassapa yang hidup di abad ke-5 SM. Purana Kassapa mengajarkan bahwa karma itu tidak ada. Setiap keburukan (doṣa) bukan "upah keburukan" (pāpakarma) sebelumnya, dan tidak akan membuahkan keburukan selanjutnya. Begitu juga setiap kebaikan (yáthā) bukan "buah dari kebaikan" (dharmaphāla) sebelumnya, dan tidak akan membuahkan kebaikan selanjutnya. Purana Kassapa melihat ketidak-terkaitan antara kejahatan dan kebaikan sebelumnya dengan kejahatan dan kebaikan selanjutnya. Hanya saja, kita tidak mengetahui secara pasti keyakinan dan ajaran Purana Kassapa, kecuali hanya dari perspektif Buddhisme. Dalam Samaññaphala Sutta (Dīgha Nikāya 2), tercatat bahwa raja Ajataṣatru (492-460 SM) dari Magadha dikunjungi oleh Devadatta, sepupu sekaligus murid Sang Buddha. Dalam dialog keduanya, Devadatta menceritakan kesaksiannya ketika bertemu dengan Purana Kassapa sbb:
"Yang Mulia Baginda Raja, suatu ketika aku mendekati Purana Kassapa, dan saat aku tiba [di tempatnya], aku menyalaminya dengan hormat. Setelah menyapanya dengan hangat dan hormat, aku duduk di sebelahnya. Setelah aku duduk, aku bertanya kepadanya: "Baginda Kassapa, di sini ada banyak pengrajin... mereka hidup dengan buah dari hasil kerajinan tangan mereka yang tampak saat ini dan sekarang... lantas, bisakah engkau menunjukkan buah dari hasil pertapaan [engkau] yang tampak saat ini dan sekarang?".
Kemudian setelah itu, Purana Kassapa berkata kepadaku: "Wahai Baginda [Devadatta], dalam bertindak atau menggerakkan orang lain untuk bertindak, dalam memotong-motong tubuh atau menggerakkan orang lain untuk memotong-motong tubuh, dalam menganiaya atau menggerakkan orang lain untuk menganiaya, dalam bersedih atau menggerakkan orang lain untuk bersedih, dalam menyiksa atau menggerakkan orang lain untuk menyiksa, dalam mengancam atau menggerakkan orang lain untuk mengancam, dalam merebut nyawa, merampas apa yang tidak diberikan, merusak perumahan, menjarah harta-benda, merampok, menghadang [rombongan pedagang] di jalan, berzina, berkata dusta, maka orang [yang melakukan] itu tidak akan mendapatkan kejahatan (doṣa). Jika dengan cakram tajam seseorang dapat mengubah seluruh makhluk di muka bumi ini menjadi setumpuk daging, menjadi potongan-potongan daging, itu semua tidak disebabkan oleh doṣa sebelumnya, dan tidak akan mendatangkan doṣa [setelahnya]. Bahkan jika seseorang mendatangi sisi kanan sungai Ganga, lalu membunuh atau menggerakkan orang lain untuk membunuh, memotong-motong tubuh atau menggerakkan orang lain untuk memotong-motong tubuh, menyiksa atau menggerakkan orang lain untuk menyiksa, maka tidak disebabkan oleh doṣa, dan tidak pula mendatangkan doṣa. Bahkan jika seseorang mendatangi sisi kiri sungai Ganga, menderma (dharma/dhamma) atau menggerakkan orang lain untuk menderma, memberikan sesajian atau menggerakkan orang lain untuk memberikan sesajian, maka tidak disebabkan oleh kebaikan (yáthā), dan tidak pula mendatangkan buah (phāla). Melalui kemurahan hati, pengendalian diri, kelapangan dada, dan kejujuran tutur kata, perbuatan itu tidak disebabkan oleh dharma, dan tidak pula mendatangkan phāla".
Jadi, ketika aku bertanya tentang buah dari pertapaannya yang terlihat saat ini dan sekarang, Purana Kassapa menjawab dengan tidak ada tindakan. Seolah-olah seperti seseorang yang bertanya tentang buah mangga, maka dia menjawabnya dengan buah sukun; atau, jika bertanya tentang buah sukun, maka dia menjawabnya dengan buah mangga. Demikianlah ketika aku bertanya tentang buah pertapaannya, Purana Kassapa menjawabnya dengan diam. Seketika terlintas dalam benakku: "Bagaimana bisa orang seperti aku memandang remeh para Brahmaṇa, atau menganggap para pertapa ini hidup dalam alam [khayalan]-nya sendiri". Namun aku tidak menerima jawaban Purana Kassapa, dan tidak pula membantahnya. Alih-alih tidak menerimanya dan tidak pula membantahnya, aku justru tidak merasa puas. Tanpa menunjukkan rasa tidak puas, tanpa menerima ajarannya, tanpa menyetujuinya, aku hanya beranjak dari dudukku dan pamit".
Kemudian setelah itu, Purana Kassapa berkata kepadaku: "Wahai Baginda [Devadatta], dalam bertindak atau menggerakkan orang lain untuk bertindak, dalam memotong-motong tubuh atau menggerakkan orang lain untuk memotong-motong tubuh, dalam menganiaya atau menggerakkan orang lain untuk menganiaya, dalam bersedih atau menggerakkan orang lain untuk bersedih, dalam menyiksa atau menggerakkan orang lain untuk menyiksa, dalam mengancam atau menggerakkan orang lain untuk mengancam, dalam merebut nyawa, merampas apa yang tidak diberikan, merusak perumahan, menjarah harta-benda, merampok, menghadang [rombongan pedagang] di jalan, berzina, berkata dusta, maka orang [yang melakukan] itu tidak akan mendapatkan kejahatan (doṣa). Jika dengan cakram tajam seseorang dapat mengubah seluruh makhluk di muka bumi ini menjadi setumpuk daging, menjadi potongan-potongan daging, itu semua tidak disebabkan oleh doṣa sebelumnya, dan tidak akan mendatangkan doṣa [setelahnya]. Bahkan jika seseorang mendatangi sisi kanan sungai Ganga, lalu membunuh atau menggerakkan orang lain untuk membunuh, memotong-motong tubuh atau menggerakkan orang lain untuk memotong-motong tubuh, menyiksa atau menggerakkan orang lain untuk menyiksa, maka tidak disebabkan oleh doṣa, dan tidak pula mendatangkan doṣa. Bahkan jika seseorang mendatangi sisi kiri sungai Ganga, menderma (dharma/dhamma) atau menggerakkan orang lain untuk menderma, memberikan sesajian atau menggerakkan orang lain untuk memberikan sesajian, maka tidak disebabkan oleh kebaikan (yáthā), dan tidak pula mendatangkan buah (phāla). Melalui kemurahan hati, pengendalian diri, kelapangan dada, dan kejujuran tutur kata, perbuatan itu tidak disebabkan oleh dharma, dan tidak pula mendatangkan phāla".
Jadi, ketika aku bertanya tentang buah dari pertapaannya yang terlihat saat ini dan sekarang, Purana Kassapa menjawab dengan tidak ada tindakan. Seolah-olah seperti seseorang yang bertanya tentang buah mangga, maka dia menjawabnya dengan buah sukun; atau, jika bertanya tentang buah sukun, maka dia menjawabnya dengan buah mangga. Demikianlah ketika aku bertanya tentang buah pertapaannya, Purana Kassapa menjawabnya dengan diam. Seketika terlintas dalam benakku: "Bagaimana bisa orang seperti aku memandang remeh para Brahmaṇa, atau menganggap para pertapa ini hidup dalam alam [khayalan]-nya sendiri". Namun aku tidak menerima jawaban Purana Kassapa, dan tidak pula membantahnya. Alih-alih tidak menerimanya dan tidak pula membantahnya, aku justru tidak merasa puas. Tanpa menunjukkan rasa tidak puas, tanpa menerima ajarannya, tanpa menyetujuinya, aku hanya beranjak dari dudukku dan pamit".
Dari testimoni Devadatta di atas, setidaknya kita memperoleh 2 (dua) petunjuk:
- Bahwa gagasan non-karma, atau non-reward and punishment, dianut oleh sebagian pertapa Śramaṇa, dan salah satu tokoh terkemukanya adalah Purana Kassapa.
- Bahwa para pertapa Śramaṇa memiliki keragaman pemikiran dan pengetahuan filosofi yang sebenarnya tidak dipandang remeh pada saat itu, terlepas dari benar salahnya.
Pada abad ke-5 SM, Purana Kassapa merupakan salah seorang dari 6 (enam) pertapa Śramaṇa yang paling menonjol saat itu, yang hidup relatif sezaman, atau lebih tua, dengan Sang Buddha. Purana Kassapa konon dianggap "mengetahui segala sesuatu" (omniscient). Dia dikabarkan mati bunuh diri dengan cara menenggelamkan diri sendiri. Akan tetapi, sekali lagi bahwa segala informasi tentang Purana Kassapa hanya diperoleh dari catatan Jainis dan Buddhis, dimana ajaran dan mimiknya digambarkan dalam kerangka polemik. Sangat sulit bagi kita untuk merekonstruksi ajarannya tanpa bias perspektif Jainisme dan Buddhisme.
Pertapa Śramaṇa kedua yang hidup di zaman yang relatif sezaman dengan Sang Buddha, adalah Makkhali Gosala, sang pertapa bertelanjang bulat. Dia diketahui mendirikan aliran Ajivika, sebuah aliran filsafat dan pertapaan yang mengajarkan doktrin filsafat fatalisme. Doktrin fatalisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa manusia tunduk pada ketetapan alamiah, sebagaimana alam semesta yang tunduk dengan hukum keteraturan alam yang tetap. Lebih jauh, sekte Ajivika meyakini bahwa manusia tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan apa-apa untuk menghindari kesengsaraan (saṃsāra), dimana saṃsāra dipandang sebagai suatu keniscayaan yang tidak dapat ditolak, sebagai hukum alam yang telah ada demikian adanya, tidak bisa dicegah, tidak bisa dilawan, dan tidak ada satupun manusia yang bisa membebaskan diri dari saṃsāra. Dalam hal ini, bagi Ajivika, mokṣa/mukti (pencerahan/pelepasan/pembebasan) dipandang bukan melepaskan saṃsāra, melainkan menerima saṃsāra. Artinya, dalam tradisi Ajivika, seseorang yang tercerahkan adalah orang yang mampu menyadari kesengsaraan sebagai realita yang niscaya/mutlak. Sekte ini masih dapat ditemui sampai abad ke-2 SM, hingga kemudian punah. Namun walaupun punah, filsafat fatalisme yang diusungnya telah menginspirasi munculnya pemahaman determinisme yang umumnya dianut sebagian besar sekte-sekte agama-agama Abrahamik, bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas (free will), bahwa manusia tunduk pada apa yang telah ditetapkan Tuhan secara mutlak kepada masing-masing individu manusia, bahwa Tuhan berkuasa mengatur segala hati, pikiran, kehendak, dan tindakan manusia.
Sebagaimana Purana Kassapa, riwayat hidup Makkhali Gosala juga bertumpu pada tradisi lainnya, yaitu tradisi Jainisme. Dalam sutra-sutra Jain, diceritakan bahwa Makkhali Gosala lahir di sebuah desa bernama Saravana (bahasa Prakerta, yang artinya: "semak belukar", sepadan dengan bahasa Sansekerta: Sarāvārna). Ibunya bernama "Bhadda" (kata ini biasanya disebutkan untuk orang-orang yang tidak dikenal, sepadan dengan kata "polan" dalam bahasa Batak, atau "kisanak" dalam bahasa Kawi, atau "adinda" dalam bahasa Melayu, atau "fulan/fulanah" dalam bahasa Arab). Sedangkan ayahnya bernama Mankhali ("ahli pertapa", mankha = tapa/hidup selibat). Nama aslinya adalah Makkhali, sementara Gosala artinya "kandang lembu". Baik tradisi Jain maupun Buddhis, Makkhali lahir di sebuah kandang lembu karena kedua orangtuanya tidak dapat menemui gubuk yang layak untuk bersalin di desa Saravana. Namun, Buddhaghosa berpendapat bahwa Makkhali lahir dari kalangan budak. Buddhaghosa menceritakan bahwa ketika Makkhali masih menjadi budak, dia seringkali disiksa oleh tuannya. Kemudian dia memutuskan untuk melarikan diri, namun dia ditarik jubahnya oleh tuannya hingga robek, dan akhirnya melarikan diri dengan bertelanjang. Buddhaghosa memang cenderung negatif dalam menggambarkan figur Makkhali Gosala. Dengan mengandung genre sastra tragedi, Buddhaghosa menggambarkan doktrin fatalisme yang diajarkannya didasari oleh kegagalannya dalam membebaskan kesengsaraan yang telah diterimanya sejak lahir.
Menariknya, Makkhali Gosala pernah berguru dengan sang pendiri Jainisme, Mahavira (w. circa 468 SM), setelah Mahavira menjadi pertapa pengembara selama 3 (tiga) tahun pertamanya. Dia berguru dengan Mahavira selama 6 (enam) tahun, dan menjadi salah seorang muridnya yang paling cerdas. Namun, tradisi Jainisme tetap menggambarkan figur Makkhali Gosala dalam kerangka polemik antara Jainisme dengan Ajivika. Diceritakan bahwa Mahavira memiliki kesaktian dalam meramalkan apapun yang akan terjadi sekalipun hal-hal kecil. Namun, Makkhali meragukan kesaktiannya, dan seringkali berusaha menggagalkan nubuatan Mahavira. Motivasi Makkhali untuk senantiasa menggagalkan nubuatan Mahavira adalah disebabkan oleh keyakinan fatalisme yang telah dianutnya, dan seringkali dia mendebat Mahavira gurunya tentang hal itu. Karena dia sendiri diceritakan selalu gagal dalam menggagalkan segala nubuatan Mahavira, maka dia memutuskan untuk berhenti berguru kepada Mahavira.
Bagaimanapun legendarisnya figur Makkhali Gosala, dengan segala mitos yang digambarkan secara polemik oleh tradisi Jainisme dan Buddhisme, namun Makkhali Gosala disepakati sebagai figur historis, dengan memisahkan unsur mitologisnya. Sekte Ajivika yang bertahan sampai dengan abad ke-2 SM memang seringkali terlibat dalam perdebatan dengan para pendeta Jain dan bhikkhu-bhikkhu Buddha sepanjang abad ke-4 sampai 2 SM. Salah satu doktrin di dalam Ajivika adalah niyativada, bahwa seluruh manusia tidak memiliki kehendak bebas menentukan pilihan mereka. Doktrin ini diketahui dari catatan-catatan Jain dan Buddha yang berusaha mendeskripsikan ajaran mereka dan mengkritiknya, itu sebabnya doktrin niyativada digambarkan dalam kerangka polemik, sehingga banyak sejarahwan tidak dapat memastikan jenis fatalisme apa yang dianut oleh sekte Ajivika.
Pertapa Śramaṇa ketiga yang hidup di zaman yang relatif sezaman dengan Sang Buddha adalah Ajita Kesakambali. Dalam catatan Jainis dan Buddhis, dia diketahui membentuk sebuah aliran yang disebut Lokayata (Charvaka), sebuah aliran filsafat yang mengusung filsafat materialisme kuno. Aliran ini mengusung doktrin bahwa realitas merupakan pencerapan langsung apa adanya, dimana materi merupakan jati diri realitas yang sebenarnya. Mereka menolak ritual (upachara) dan hal-hal supranatural. Mereka memahami Veda sebagai teks yang penuh makna tersembunyi (metafora) dari setiap petuahnya, yang sebenarnya menggambarkan materi adalah realitas asli semesta. Menurut tradisi Veda, Brihaspati (Jupiter) adalah pendiri dari aliran Charvaka. Namun, sejarahwan lebih sepakat bahwa aliran ini baru muncul tidak lebih awal dari abad ke-7 SM, dan Ajita Kesakambali adalah figur utama dari peletak dasar doktrin Lokayata. Meskipun bertentangan dengan Veda, namun aliran Lokayata sebenarnya menerima Veda sebagai petunjuk, walau tidak memiliki otoritas. Bagi penganut Charvaka, pencerahan tidak diperoleh melalui ritual dan kepercayaan, melainkan melalui pengalaman. Pada fase selanjutnya, sebagian pertapa Charvaka banyak yang bersinkretis dengan Jainisme dan Buddhisme. Sedikit sekali informasi yang diperoleh tentang Ajita Kesakambali, namun aliran Lokayata yang didirikannya ini dapat digolongkan sebagai mazhab materialisme tertua yang diketahui sepanjang sejarah manusia.
BACA JUGA :
Nāstika dan Śramaṇa Awal (2)

Selanjutnya, pertapa Śramaṇa keempat yang tidak kalah misteriusnya adalah Pakkudha Kaccayana, atau Kadhudha Katiyana. Dia juga hidup relatif sezaman dengan Mahavira dan Buddha. Meskipun tidak ditemukan riwayat hidup yang jelas tentang Pakkudha, namun ajarannya dapat ditemui secara polemik dalam teks-teks Jain dan Kanon Pali Buddha. Dia diketahui mendirikan aliran Sassatavada, sebuah aliran filsafat atomisme yang memandang bahwa terdapat 7 (tujuh) elemen dasar pembentuk alam semesta yang abadi, yaitu:
- Tanah/bumi.
- Air.
- Api.
- Udara.
- Kebahagiaan.
- Penderitaan.
- Jiwa (jivā).
Dalam Samaññaphala Sutta (Dīgha Nikāya 2), terdapat atestasi sbb:
"Pakkudha Kaccayana berkata: "Ada tujuh zarah, yang tidak dapat dibentuk, tidak dapat dirusak, tidak dapat diciptakan, tanpa pencipta, sunyi, yang tidak berubah seperti pegunungan, dan berdiri tegak seperti tiang. Ketujuh zarah itu tidak dapat mewujud, tidak dapat diubah, tidak ada campur tangan atasnya, tidak dapat memberikan kesenangan, tidak dapat memberikan rasa sakit, dan tidak dapat memberikan keduanya. Tahukah kamu apa ketujuh zarah itu? Mereka adalah zarah tanah, zarah cair, zarah api, zarah udara, kesenangan, penderitaan, dan jiwa. Inilah ketujuh zarah dasar yang: tidak dapat dibentuk, tidak dapat dirusak, tidak dapat diciptakan, tanpa pencipta, sunyi, tidak berubah seperti pegunungan, dan berdiri tegak seperti tiang".
Pertapa Śramaṇa selanjutnya, yang kelima, tidak lain adalah sang pertapa kharismatik Mahavira (w. circa 468 SM, atau abad ke-5 menurut tradisi Jainisme). Sebagaimana umumnya pertapa yang mengajarkan dharma lainnya, Mahavira juga pada akhirnya mendirikan Jainisme yang meyakini bahwa saṃsara dapat dihindari apabila manusia berhasil mencapai mokṣa/mukti, sama seperti Buddhisme. Hanya saja, Jainisme menganut doktrin anti-kejahatan dengan interpretasi "kejahatan" yang sangat ketat, yang saking ketatnya, memakan sesuatu saja sudah merupakan bentuk dari kejahatan. Meskipun dia dikenal sebagai pendiri Jainisme, namun dia dipercaya hanya meneruskan ajaran Tirthankara terdahulu. Tirthankara adalah istilah bagi para mahaguru pertapa yang mengajarkan manusia untuk melepaskan saṃsara dengan membangun keberlepasan diri terhadap nafsu dan ego, dan Mahavira adalah Tirthankara ke-24.
Kisah hidup Mahavira sepenuhnya mengandalkan tradisi Jainisme. Dia konon bernama asli Vardhamana, yang lahir dari kasta Kṣatriya, putra dari raja Siddhartha (Siddhartharaja) dan ratu Trishala di Kundagrama, Vaishali (sekarang Vajji di Bihar, India). Dia disebut juga sebagai Nigaṇṭha Nātaputta / Nigaḍa Nātaputtra yang artinya: "Si Kalung Besi Putra Terhormat" yang secara ekspresif melambangkan kastanya. Vardhamana sendiri dipercaya yang telah melalui 26 kelahiran sebelumnya, yaitu yang paling pertama sebagai penghuni neraka (nárakarṇava), sempat bereinkarnasi menjadi singa, dan menjadi tuhan (deva) pada kelahirannya yang ke-26, sebelum akhirnya lahir sebagai Vardhamana.
Masih dalam tradisi Jainisme. Mirip seperti kisah hidup Sang Buddha, Vardhamana menghabiskan masa kecil dan mudanya dengan hidup berkemewahan di istana ayahnya, Siddhartha sang Raja Kundagrama. Namun, dia juga tidak merasakan kebahagiaan dengan yang dimilikinya, dan memutuskan untuk hidup bertapa dan meninggalkan kemewahannya di usia 30 tahun, termasuk istrinya (Yashoda) dan putrinya (Priyadarṣana/Anojja). Pada masa awal pertapaannya, dia memilih jalan penderitaan untuk pertapaannya, seperti berdiri satu kaki di atas batu di bukit tanpa duduk sekalipun, bergelantungan di pepohonan dengan kakinya secara terbalik, dan bahkan tidur di atas tumpukan daun kering yang dikerubungi semut siang-malam berpuasa tanpa makan-minum sedikitpun. Namun, suatu ketika dia duduk di bawah pohon Aṣoka dalam keadaan kurus kering dan bertelanjang, dan di sanalah dia memperoleh pencerahan/pengetahuan sejatinya yang disebut kevala jñāna. Dia pun memutuskan untuk hidup berpuasa sepenuhnya seumur hidup dan tanpa mengenakan sehelai pakaian sedikitpun untuk menjaga pengetahuan sejatinya dan untuk mempersiapkan mokṣa/mukti. Dengan itu pula, dia dipercaya memiliki sifat ke-maha-mengetahui-an (omniscient).
Setelah itu, dia memutuskan untuk mengembara menyebarkan ajarannya yang kemudian dikenal sebagai Jainisme. Masih menurut tradisi Jain, dia memperoleh 11 murid dari kalangan Brāhmaṇa, yaitu: Agnibhuti, Vayubhuti, Akampita, Arya Vyakta, Sudharmana, Manditaputtra, Mauryaputtra, Acalabhrata, Metraya, dan Prabhasa. Bersama kesebelas muridnya, dia berhasil membangun perguruan asketiknya. Menurut tradisi Jain, dia memiliki 14.000 sādhu (para pendeta laki-laki), 36.000 sādhvi (para pendeta perempuan), 159.000 śrāvaka (pengikut laki-laki), dan 318.000 śrāvikā (pengikut perempuan). Para pengikutnya konon membangun Samavasarana, sebuah stupa beranak-tangga 30.000 dimana dia berkhotbah terakhir kalinya di sana. Dia "wafat" (mokṣa atau mencapai nirvana) di Pavapuri (sekarang Bihar, India) dan akhirnya terbebas dari saṃsara (tidak akan bereinkarnasi lagi).
Dalam sejarah kritis, Mahavira historis hidup di abad ke-4 SM, atau sekitar dari tahun 540-486 SM. Hal ini berdasarkan bukti arkeologis dari Prasasti Barli (circa berbahasa Prakerta yang menyebutkan kalimat Viraya Bhagavate chaturasiti vase, yang artinya: (1) "dipersembahkan untuk Baginda Vira pada usianya yang kedelapan puluh empat", yang maksudnya adalah 84 tahun setelah nirvana-nya, sehingga bila dihitung mundur dari 443 SM, maka dia wafat pada tahun 486 SM. Namun, tradisi Jainisme tidak dapat diabaikan begitu saja. Tradisi Jainisme mengandalkan sepenuhnya teks-teks sutra/sutta yang tersebar secara acak sepanjang abad ke-4 SM. Sebagian besar kisahnya yang cenderung supranatural dapat dianggap sebagai mitos/legenda (termasuk "kemewahan" yang pernah dimilikinya), namun karena sutra-sutra yang tersebar itu mencatat berbagai peristiwa berbeda, maka dapat dipastikan bahwa para pencatat sutra Jain memang pernah menemuinya selama singgah dalam pengembaraannya. Artinya, pengembaraan Mahavira dapat dipastikan historis. Sebutan Śramaṇa dalam teks-teks Buddhisme juga menyiratkan pengembaraannya tsb.
Berikutnya, pertapa Śramaṇa keenam yang mungkin paling menarik dan tampaknya paling tua dari antara kelima pertapa Śramaṇa lainnya, adalah Sañjaya Vairatiputra (dalam teks Pali: "Sanjaya Belatthaputta") yang hidup sekitar abad ke-6 SM. Dia diketahui membangun aliran Ajñana, sebuah sekolah kuno yang bercorak skeptisisme. Sedikit sekali kita mengetahui secara persis bagaimana ajarannya. Namun konon 2 (dua) orang murid Sang Buddha pernah berguru dengannya, yaitu Maudgalyāyana dan Śāriputra. Dan kita menemukan catatan dalam tradisi Buddhisme, bahwa Sañjaya Vairatiputra pernah berpetuah dalam Samaññaphala Sutta (Dīgha Nikāya 2) sbb:
"Jika kamu menanyakan apakah ada dunia lainnya [setelah kematian], jika aku memikirkan bahwa dunia lain itu ada, mungkinkah aku akan memberitahukannya kepadamu? Kurasa tidak. Aku tidak akan memikirkan hal itu, [juga] tidak memikirkan sebaliknya. Aku tidak berpikir tidak, [juga] tidak untuk tidak berpikir tidak. Jika kamu menanyakan apakah tidak ada dunia lain [setelah kematian]... keduanya ada dan tidak ada... tidak pula ada ataupun tidak ada... apakah ada makhluk yang singgah [ke sana].... apakah tidak ada... ataukah tidak pula ada maupun tidak ada... apakah Tathāgataada setelah kematiannya... tidak ada... keduanya... ataukah ada maupun tidak ada, akankah aku memberitahukannya kepadamu? Kurasa tidak. Aku tidak akan memikirkan hal itu, [juga] tidak memikirkan sebaliknya".
Dalam teks Kanon Pali lainnya, yaitu Dhammajāla (Dīgha Nikāya 1) menyebut doktrin yang diajarkan Sañjaya sebagai amarāvikkhepavāda ("berdalih tanpa ujung"). Dalam hal ini, gagasannya condong bercorak agnostik, yakni sebuah gagasan filsafat yang percaya bahwa tidak ada satupun manusia yang mengetahui, baik dapat mengetahui maupun telah mengetahui, tentang apapun selain dari realitas sekarang. Meskipun tradisi Buddhisme menggambarkan ajaran Sañjaya dalam kerangka polemik dengan Buddhisme, namun apabila disandingkan dengan tradisi Jainisme, maka tampaknya doktrin agnostik memang doktrin yang diusung oleh Sañjaya. Dalam Sūtrakṛtāṅga (salah satu sutra Jain), disebutkan bahwa Śīlāṅka (salah seorang pendeta Jain paling awal) menyampaikan tanggapan terhadap berbagai komentar dari kalangan skeptis yang disebut-sebut sebagai "ajñānikāh/ajñānikāh" (secara harfiah artinya: "kalangan yang meragukan/tidak berpengetahuan"; jñana artinya "pengetahuan"), yang tampaknya merupakan formasi awal sekte Ajñana. Namun, istilah ini juga bukan merupakan tiponimi/nama baku, melainkan sebutan yang peyoratif terhadap kelompok skeptis ini untuk semata-mata menyudutkan mereka sebagai orang-orang yang bodoh. Dalam hal ini, Sūtrakṛtāṅga merangkum beberapa kritik terhadap kelompok "ajñānikāh/ajñānikāh" ini dari Śīlāṅka dimana kebanyakan kritikan tsb mengandung: (1) argumen kelompok "ajñānikāh/ajñānikāh" melawan teks-teks Rígveda, (2) tanggapan Śīlāṅka, dan (3) penukilan teks-teks Upaniṣad dari Śīlāṅka (tradisi Jainisme masih menggunakan pernyataan-pernyataan Upaniṣad yang filosofis dan multitafsir sebagai pendukung ajaran mereka).
Meskipun digambarkan secara negatif oleh tradisi Jainisme dan Buddhisme, namun ajaran Sañjaya Vairatiputra dapat dikategorikan sebagai skeptisme paling awal sepanjang sejarah, mendahului dialektika sokratik yang diajarkan Socrates (w. 399 SM) dan skeptisme pyrrhonian yang diajarkan Pyrrho (w. 270 SM). Bahkan, ajarannya memiliki jejak pengaruh ke Yunani yang tidak bisa disangkal (akan dibahas pada bab Periode Indo-Yunani / Greco-Buddhisme). Mungkin terlalu berlebihan jika dikatakan Sañjaya yang mempeloporinya, namun paling tidak, walau boleh dikatakan gagasan skeptis sudah ada jauh sebelum dia, namun dialah yang tampaknya berperan aktif menyebarluaskan gagasan ini secara lebih terorganisir dan lebih akademis.
Dan terakhir, pertapa Śramaṇa yang ketujuh yang sezaman dengan Sang Buddha, adalah Sang Buddha sendiri. Meskipun sebutan Śramaṇa bagi Sang Buddha tidak pernah dikenal dalam tradisi Buddhisme (dan bahkan Jainisme), namun tidak dapat dipungkiri bahwa dia sendiri adalah pertapa Śramaṇa. Nama aslinya Siddhartha Gautama (w. circa 438-400 SM) yang juga berasal dari kasta Kṣatriya. Beberapa argumen sejarahwan untuk menempatkan namanya sebagai seorang pertapa Śramaṇa, didasari oleh beberapa fakta berikut:
- Tradisi Buddhisme menggambarkan Siddhartha Gautama sebagai seorang Kṣatriya yang juga sedang mencari pengetahuan sejati untuk membebaskan diri dari saṃsara dan mencapai mokṣa/mukti (dalam tradisi Buddhisme disebut sebagai parinibbāna; Sanskerta: parinirvāṇa). Trend serupa yang ditemukan pada pertapa-pertapa Śramaṇa lainnya.
- Catatan-catatan Yunani yang menggunakan istilah "Sarmanae" (Σαρμάναι) dan "Bouddo" (Βóδδο) secara bergantian (akan dibahas lebih detil pada bab Indo-Yunani/Greco-Buddhisme).
Tradisi Buddhisme menceritakan Siddhartha Gautama lahir di bawah pohon Sala/Sarai di taman Lumbini yang berlokasi di kaki gunung Himalaya di India utara (sekarang Nepal). Dia adalah putra dari raja Śuddhodana dari Kapilavastu (dinasti Ṣakya) dan ratu Māyā (Māyādēvi). Sebagaimana Mahavira dalam tradisi Jainisme, kelahirannya juga dipenuhi legenda supranatural. Konon ketika dia lahir, dua arus mata air kecil jatuh dari langit, yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Kedua arus tsb membasuhi tubuh Siddhartha bayi. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak, dan langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Sebenarnya banyak sekali keajaiban kelahirannya yang dikisahkan tradisi Buddhisme, namun yang paling umum adalah kisah di atas.
Sebagaimana Mahavira dalam tradisi Jainisme, Siddhartha dalam tradisi Buddhisme juga dibesarkan di lingkungan kemewahan kerajaan ayahnya. Namun, dia tumbuh dengan pribadi yang santun, jujur, dan halus. Itulah sebabnya, dia dapat merenungkan banyak hal di masa mudanya. Dalam teks-teks Pali tertua, yaitu dalam Ariyapariyesanā Sutta (MN 26), dikisahkan bahwa pangeran Siddhartha pada mulanya merenungi tentang kelahiran dan kematian, dimana dia menemukan fakta bahwa kelahiran dan kematian adalah belenggu kesengsaraan manusia, sehingga dia memutuskan untuk mencari cara bagaimana manusia bisa terlepas dari belenggu tsb, dan dimulailah pengembaraannya sebagai pertapa. Namun, pada teks-teks belakangan yang lebih populer, dikisahkan bahwa pangeran Siddhartha sedang berkeliling keluar istana. Dan untuk pertama kalinya dia melihat ada orang yang sedang sakit dan orang tua renta. Pengawalnya menjelaskan bahwa setiap orang bisa suatu waktu menderita suatu penyakit, juga setiap orang akan menua, dan tidak ada satupun manusia yang bisa terbebas dari kedua penderitaan itu. Kemudian, pangeran Siddhartha melihat seorang pertapa, dan pengawalnya menjelaskan bahwa para pertapa berusaha mencari cara bagaimana agar manusia terbebas dari penderitaan. Akhirnya, sang pangeran memutuskan untuk menjadi pertapa. Sementara itu, dalam teks lain diceritakan bahwa seorang peramal pernah menubuatkan di depan raja Śuddhodana, bahwa kelak pangeran Siddhartha akan membebaskan manusia dari penderitaan. Sang raja berpikir bahwa, maksudnya, anaknya akan menjadi maharaja yang akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Namun tidak disangka bahwa pertapaan-lah jalan yang dipilih oleh sang pangeran. Pangeran Siddhartha meninggalkan istrinya, putri Yaṣodhara dan putranya, Rāhula, meninggalkan kemewahan istananya, dan memulai hidup selibat.
Sebagaimana Mahavira dalam tradisi Jainisme, tradisi Buddhisme juga menceritakan Siddhartha memulai pertapaannya dengan sangat menderita. Dalam 7 (tujuh) tahun pertamanya, dia menjalani pertapaan yang menyiksa diri di bawah bimbingan 2 (dua) orang pertapa, yaitu Aradha Kalama dan Udraka Ramaputra. Dia bahkan juga memutuskan untuk berpuasa tanpa sedikitpun berbuka. Namun, suatu ketika dia didatangi seorang perempuan desa bernama Sujata dan memberinya secawan bubur. Siddhartha kemudian menyadari bahwa pertapaan semacam itu sia-sia dan tidak akan membawa pencerahan sama sekali. Akhirnya, dia memutuskan untuk bertapa dengan cara duduk diam saja di bawah sebuah pohon Ara besar yang dikenal sebagai pohon Bodhi ("pohon pengetahuan/pencerahan") yang terletak di Bihar, India.
BACA JUGA :
Śramaṇa Dalam Catatan Yunani

Sejak abad ke-4 SM, Śramaṇa bertransformasi menjadi sebuah gerakan pertapaan bebas yang dipraktikan pertapa-pertapa dari kalangan non-Brāhmaṇa. Pertapaan mereka meliputi: (1) tanpa mazhab/aliran, (2) sinkretisme dengan Buddhisme, (3) sinkretisme dengan Jainisme, (4) sinkretisme Buddhisme-Jainisme. Dan keadaan menjadi lebih unik ketika pengaruh Yunani merasuk sejak abad ke-3 SM sehingga memainkan peranan besar dalam transfer spiritual dari timur ke barat. Periode ini dikenal sebagai Greco-Buddhisme / Indo-Yunani (greco = greek, indo = india). TS sudah pernah membahas periode ini di thread: Kebudayaan Greco-Buddhisme, Ketika Yunani dan India Bercumbu Mesra, dan TS sangat merekomendasikan untuk agan-agan membaca thread tsb untuk mengetahui lebih spesifik tentang asimilasi Yunani dengan India ini.
Catatan-catatan Yunani menyebutkan sekelompok pertapaan di Bactria (Balkh) dan Transoxiana, yang disebut Sarmanae (Σαρμάναι), atau Sarmanae Bouddo (Σαρμάναι Βóδδο). Dan banyak di antara filsuf Yunani berguru, atau menerima pengetahuan filsafat dari Sarmanae ini. Para filsuf yang terinspirasi dari Sarmanae ini kemudian dikenal sebagai Gymnosofis (filsuf tanpa mazhab/aliran). Gaya hidup dan corak pemikiran tentang pelepasan kesengsaraan, hidup berkesederhanaan, dan keyakinan tentang adanya kebenaran sejati yang bersifat transenden adalah gaya hidup dan corak dari Śramaṇa, yang kemudian mempengaruhi spiritualisme di Yunani, termasuk Anatolia, Persia, Mesir, dan Syria (Near East). Pada periode selanjutnya, bahkan setelah memasuki pemerintahan 'Abbasiyyah, pertapa Śramaṇa masih dapat ditemui meskipun sebagian besar telah bertransformasi menjadi bhikkhu-bhikkhu pengembara.
Sebagian besar catatan Yunani pada awal abad ke-1 M umumnya ditemukan dalam penyebutan sekelibat saja. Beberapa di antaranya adalah Clementus dari Alexandria (w. 211), seorang penulis Kristen yang menulis dalam esainya, Stromata Vol. 1 Bab 15 Hal. 398-399 sbb:
"Filsafat itu sesuatu yang memiliki manfaat yang luhur, berkembang di zaman kuno di antara orang-orang barbar, memancarkan cahayanya ke atas segala bangsa. Dan setelah itu datang ke Yunani. Filsuf pertama adalah deretan para nabi orang-orang Mesir; dan orang-orang Kasdim di antara orang-orang Asyur; dan orang-orang Druid di antara orang-orang Galia; dan orang Samanaioi (Σαμαναίοι)di antara orang-orang Bactria; dan para filsuf Kelt; serta orang-orang Majus dari Persia yang meramalkan kelahiran Sang Juruselamat, dan datang ke tanah Yudea dengan dipandu oleh sebuah bintang. Para gymnosofis India juga ada dalam kelompok itu, dan para filsuf orang-orang barbar lainnya. Dan di antaranya ada dua kelas, beberapa di antaranya disebut Sarmanae (Σαρμάναι) dan Brahmanae (Βραχμαναι)"
Lalu, Porphyrius (w. 305), sang filsuf yang terbiasa mengkritik Kekristenan dan berpolemik dengan komunitas gereja saat itu, mencatat kebiasaan dan gaya hidup para pertapa Śramaṇa dengan cukup detil. Dalam esainya, Peri Apokhis IV, Porphyrius menulis sbb:
"Terhadap pemerintahan orang India yang tersebar ke banyak wilayah, ada satu suku di antara mereka yang tergolong orang-orang yang bijaksana, yang oleh orang Yunani biasa disebut sebagai gymnosofis. Tetapi di antara [gymnosofis] ini ada dua sekte, yang satu dipimpin oleh para Brahmanae, tetapi yang lainnya dipimpin oleh para Samanaioi. Akan tetapi, sekte para Brahmanae menerima kebijaksanaan ilahi semacam ini secara turun-temurun, dengan cara yang sama seperti imam-imam. Tetapi orang Samanaioi dipilih, dan yang terpilih dari mereka adalah yang ingin memiliki pengetahuan ilahiah"
Lebih lanjut, Porphyrius menulis:
"Semua Brahmanae berasal dari satu wangsa; karena mereka semua berasal dari satu ayah dan satu ibu. Tetapi orang Samanaioi bukanlah keturunan dari satu keluarga, seperti yang telah kami katakan, dikumpulkan dari setiap bangsa di Hindia. Seorang Brahmanae, bagaimanapun, bukanlah bangsawan mana pun, dia juga tidak pernah menjabat suatu jabatan apapun bersama-sama dengan orang lain di dalam pemerintahan.
Orang-orang Samanaioi, seperti yang telah kukatakan, mereka dipilih. Namun, jika seseorang ingin mendaftarkan diri ke dalam ordo/tarekat mereka, orang itu haruslah setidaknya seorang penguasa kota; tetapi setelah itu dia harus meninggalkan kota atau desa yang dia huni, dan [meninggalkan] semua kekayaan dan harta lain yang dia miliki. Setelah segala pernak-pernik tubuhnya dilucuti, dia menerima jubah, dan berangkat ke menuju komunitas Samanaioi, berangkat untuk tidak kembali kepada istri dan anak-anaknya, yang jika dia kebetulan telah memiliki [istri dan anak-anaknya], juga tidak boleh memperhatikan mereka, ataupun berpikir untuk berhubungan kembali dengan dia. Dan, sehubungan dengan anak-anaknya, para raja akan menyediakan apa yang diperlukan untuk mereka, dan kerabat menyediakan keperluan untuk istri. Dan begitulah kehidupan orang Samanaioi. Tetapi mereka tinggal di luar kota, dan menghabiskan sepanjang hari dalam percakapan yang berkaitan dengan keilahian. Mereka juga memiliki pendopo dan kuil, yang dibangun oleh raja, di mana mereka adalah pelayan, yang menerima upah tertentu dari raja, dengan tujuan agar makanan tersedia bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Tetapi makanan mereka terdiri dari nasi, roti, buah-buahan musim gugur, dan rempah-rempah. Dan ketika mereka masuk ke dalam rumah mereka, suara bel menjadi tanda masuknya mereka, mereka yang bukan Samanaioi pulang, dan orang-orang Samanaioi segera mulai berdoa".
Orang-orang Samanaioi, seperti yang telah kukatakan, mereka dipilih. Namun, jika seseorang ingin mendaftarkan diri ke dalam ordo/tarekat mereka, orang itu haruslah setidaknya seorang penguasa kota; tetapi setelah itu dia harus meninggalkan kota atau desa yang dia huni, dan [meninggalkan] semua kekayaan dan harta lain yang dia miliki. Setelah segala pernak-pernik tubuhnya dilucuti, dia menerima jubah, dan berangkat ke menuju komunitas Samanaioi, berangkat untuk tidak kembali kepada istri dan anak-anaknya, yang jika dia kebetulan telah memiliki [istri dan anak-anaknya], juga tidak boleh memperhatikan mereka, ataupun berpikir untuk berhubungan kembali dengan dia. Dan, sehubungan dengan anak-anaknya, para raja akan menyediakan apa yang diperlukan untuk mereka, dan kerabat menyediakan keperluan untuk istri. Dan begitulah kehidupan orang Samanaioi. Tetapi mereka tinggal di luar kota, dan menghabiskan sepanjang hari dalam percakapan yang berkaitan dengan keilahian. Mereka juga memiliki pendopo dan kuil, yang dibangun oleh raja, di mana mereka adalah pelayan, yang menerima upah tertentu dari raja, dengan tujuan agar makanan tersedia bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Tetapi makanan mereka terdiri dari nasi, roti, buah-buahan musim gugur, dan rempah-rempah. Dan ketika mereka masuk ke dalam rumah mereka, suara bel menjadi tanda masuknya mereka, mereka yang bukan Samanaioi pulang, dan orang-orang Samanaioi segera mulai berdoa".
Kebiasaan yang dicatat oleh Porphyrius ini tidak lain adalah tradisi intelektual sangha. Adapun calon-calon Śramaṇa yang diambil dari bangsawan kota tidak lain adalah bahwa sebagian besar pertapa Śramaṇa berasal dari kasta Kṣatriya, meskipun adakalanya memang berasal dari kasta Vaiṣa. Tampaknya, kita menjadi tahu bahwa motif di balik persyaratan kasta Kṣatriya ini adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan sang calon pertapa Śramaṇa sehingga sang calon dapat fokus menjalankan kehidupan selibatnya. Kemudian, terkait dengan upah dari raja, kita sebaiknya tidak dalam rangka menyebut mereka hidup dalam banyak harta, melainkan pendermaan/donasi dari raja yang biasa dihaturkan sehari-hari. Tradisi ini disebut dāna (almsgiving), yang bisa dilakukan dengan cara: (1) individual dimana seorang sangha berkeliling desa/kota di pagi hari sambil membawa cawan kosong dan warga memberikan sumbangan beras, lauk-pauk, dll, atau dengan cara (2) kolektif dimana warga dan rombongan raja mendatangi sangharama dan memberikan sumbangan makanan. Kegiatan ini sering disalahpahami sebagai aksi mengemis, namun dari perspektif dharma, kegiatan ini adalah agar memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk berbuat kebajikan dengan cara mendonasikan harta mereka dalam bentuk makanan, sekaligus melatih sangha untuk hidup sangat sederhana. Tapi tentu saja deskripsi Porphyrius di atas lebih tampak seperti deskripsi tentang kegiatan pertapaan Buddhis daripada pertapaan Śramaṇa secara umum. Namun bukan berarti Porphyrius tidak cermat. Lebih lanjut, Porphyrius juga menulis sekelompok Śramaṇa lainnya yang tampak non-Buddhis, yang digambarkannya sebagai "mereka yang berfilsafat". Selengkapnya sbb:
"Dan bagi mereka yang berfilsafat, di antaranya ada yang berdiam di pegunungan, dan yang lain di sungai Ganga. Dan mereka yang hidup di pegunungan memakan buah-buahan musim gugur, dan susu sapi yang digumpalkan dengan tumbuh-tumbuhan. Tetapi mereka yang tinggal di dekat sungai Ganga, juga hidup dari buah-buahan musim gugur, yang diproduksi berlimpah di sekitar sungai itu. Tanah itu juga hampir selalu menghasilkan buah baru, bersama dengan banyak padi, yang tumbuh secara spontan, dan yang mereka gunakan ketika ada kekurangan buah-buahan musim gugur. Tetapi mencicipi makanan lain apa pun, atau, singkatnya, menyentuh makanan hewani, dianggap oleh mereka sama dengan ketidaksucian dan kejahatan yang ekstrem. Dan ini adalah salah satu ajaran mereka. Mereka melakukan persembahyangan dengan kesalehan dan kemurnian. Mereka menghabiskan hari, dan sebagian besar malam, dengan puji-pujian dan doa kepada para Dewa; masing-masing dari mereka memiliki pondok untuk dirinya sendiri, dan hidup sendirian. Berbeda para Brahmanae yang tidak dapat bertahan untuk hidup bersama orang lain, atau berbicara kepada banyak orang; tetapi ketika sesekali ini terjadi, para Samanaioi ini kemudian menarik diri, dan tidak berbicara selama berhari-hari. Mereka juga sering berpuasa tanpa lelah".
Sampai sini kita dapat menangkap keberadaan sekte-sekte Śramaṇa lainnya yang berada di luar dari tradisi intelektual Buddhisme. Mereka seperti pertapa pengembara sebagaimana hakikat asli mereka. Mereka umumnya cenderung menganut veganisme (tidak memakan hewan sama sekali), dan terbiasa hidup di belantara hutan dan pegunungan, atau di tepian sungai Ganga. Mereka juga "hilang-muncul", dimana jika salah seorang pertapa dari mereka muncul ke publik dan berkhotbah, keesokan harinya pertapa tsb kembali mengasingkan diri. Mereka ada ritual sembahyang yang dilakukan secara eksklusif, walau sembahyang tsb tampaknya bukan ditujukan kepada dewa-dewi tertentu melainkan salah satu bentuk "suluk" (upaya membuka tabir batin). Sebagian dari mereka ada yang membangun pondokan sendiri yang utamanya untuk mereka bertapa. Dan yang tidak kalah menarik perhatiannya adalah puasa. Ciri khas Śramaṇa ini sangat umum dijumpai, terutama bagi mereka yang menganut Jainisme.
Lebih lanjut, Porphyrius juga menulis tentang mokṣa/mukti sbb:
"Mereka begitu condong dengan kematian, sehingga mereka dengan enggan menanggung seluruh kehidupan saat ini, sebagai bentuk pengabdian tertentu kepada alam, dan karena itu mereka bergegas untuk membebaskan jiwa mereka dari tubuh. Oleh karena itu, seringkali mereka mati dalam keadaan terlihat baik-baik saja, dan tidak merasa sedang tertindas, atau terlihat putus asa oleh kejahatan, karena mereka meninggalkan kehidupan".
Selain Clementus dan Porphyrius, catatan tentang Śramaṇa dapat ditemui sangat banyak. Beberapa di antaranya misalnya dari Nicolaus dari Damaskus (w. 4), Strabo (w. 24), dan Cassius Dio (w. 235) yang mencatat tentang seorang pertapa Śramaṇa asal India yang dalam lidah Yunani bernama Zarmanochegas/Zarmarus (w. circa 19 SM). Nicolaus mencatat bahwa dia menerima kunjungan duta besar dari "Porus" di India (bisa jadi kunjungan dari kerajaan Pandya berdasarkan atestasi dari Strabo: "Pandian", atau maksudnya adalah kunjungan dari sekelompok pandita) di Antiokhia. Salah seorang duta tsb adalah seorang Śramaṇa yang disebut-sebut sebagai Zarmanochegas. Zarmanochegas juga terlihat sering bertapa di sudut jalan Antiokhia. Strabo dan Cassius Dio mencatat bahwa Zarmanochegas kemudian melanjutkan perjalanan kedutaannya sampai ke Athena, dan di sana dia melakukan aksi bakar diri. Strabo mencatat dalam kitabnya, Geographia XV.I. cf. 4 (Hal. 4-7) sbb:
"Dari suatu tempat di India, dan dari seorang raja, yaitu Pandian, atau, menurut yang lain, Porus, sejumlah hadiah dan duta besar dikirimkan kepada Kaisar Augustus. Di antara para duta besar yang datang ada pertapa India, yang membiarkan dirinya dilalap api di Athena, seperti Calanusyang menunjukkan pameran yang sama di hadapan Alexander".
Strabo juga menulis dalam Geographia XV.I cf. 73 (Hal. 124-129) sbb:
"Dia [Artemidorus] berkata bahwa saat di Antiokhia, dekat Daphne, dia berkesempatan bertemu dengan para duta besar India yang diutus kepada Kaisar Augustus, yang menurut surat resminya ada lebih dari tiga duta besar, namun yang bertahan hanya tiga orang (menurut apa yang dia saksikan), beberapa sisanya telah meninggal karena perjalanan jauh. Surat itu ditulis dalam bahasa Yunani di atas kulit, penulisnya tampaknya orang Porus sendiri, yang menyebutkan bahwa raja [Porus] adalah raja yang berdaulat di atas enam ratus raja, dan sangat berhasrat untuk bersahabat dengan Kaisar [Augustus], bahwa beliau [raja Porus] bersedia mengizinkan siapapun orang [Romawi] melintasi negaranya, di bagian manapun yang dia suka, dan bersedia membantunya di setiap usaha dengan adil. Delapan abdi telanjang dengan sabuk yang melingkari pinggang mereka serta berbagai wewangian dipersembahkan [kepada Kaisar] sebagai hadiah. Mereka juga mempersembahkan "Hermes", seorang pria tanpa lengan, dan ular besar, ular sepuluh hasta panjangnya, serta ayam hutan yang lebih besar daripada burung nasar. Mereka ditemani oleh seorang pertapa yang dikenal membakar dirinya sampai mati di Athena di kemudian hari. Dia mempraktikan laku prihatin, menjadi pelarian bagi orang-orang yang sedang dilanda malapetaka, juga menjadi jawaban bagi orang-orang yang makmur. Karena banyak orang yang sampai sekarang telah berhasil bersamanya, maka dia pikir perlu untuk mengembara, supaya jangan sampai terjadi lagi bencana tak terduga. Dengan senyumannya, dia bertelanjang, diurapi, dan dengan sabuk melingkari pinggangnya, lalu dia melompat ke atas tumpukan kayu api. Di makamnya tertulis begini: "Zarmanochegas, seorang India, asli Bargosa, telah hidup abadi, menurut adat dari negerinya, di sinilah jasadnya disemayamkan".
Makam yang dimaksud oleh Strabo tidak lain adalah sebuah tugu/prasasti nisan di Kerameikos, namun tulisan tersisa yang tertera di sana hanya: "Zarmanochegas, seorang India, asli Bargosa" (ΖΑΡΜΑΝΟΧΗΓΑΣ ΙΝΔΟΣ ΑΠΟ ΒΑΡΓΟΣΗΣ - Zarmanokhegas Indos Apos Bargoses). Nama "Bargosa" tidak lain adalah nama kota Barugaza (Bharuch) di Gujarat, India. Masih menurut Strabo di atas, tampaknya aksi bakar diri yang dilakukan oleh Zarmanochegas adalah semacam ritus mokṣa.
Sedangkan Cassius Dio yang mencatat belakangan, menulis dalam kitabnya Romaiki Istoria LIV.9 sbb:
"Karena begitu banyak duta-duta datang kepadanya, dan orang-orang India, yang telah membuat penawaran, sekarang membuat perjanjian persahabatan, mengirimkan di antara hadiah-hadiah di antaranya harimau, yang untuk pertama kalinya dilihat oleh orang-orang Romawi, kurasa demikian juga oleh orang-orang Yunani ... Salah seorang India bernama Zarmarus, untuk beberapa alasan, menghendaki mati, selain karena dia sebagai orang bijak, juga karena digerakkan oleh suatu cita-cita yang sesuai dengan kebiasaan orang-orang India di usia tua, atau karena dia ingin membuat pertunjukan kepada Augustus dan orang Athena (karena Augustus telah mencapai Athena)".
Apapun itu, Zarmanochegas dikenal sebagai seorang pertapa Śramaṇa asal India yang diketahui mengembara hingga ke Athena, baik secara resmi sebagai duta besar, maupun secara pribadi. Baik nama "Zarmanochegas" maupun "Zarmarus" tidak memiliki kesepadanan kata dengan nama orang India, baik dalam bahasa Prakerta/Sanskerta, ataupun Pali, sehingga sejumlah sejarahwan menduga nama ini bukanlah nama, melainkan suatu julukan dalam lidah Yunani. Sejumlah sejarahwan modern mencoba mengaitkan dengan beberapa kata dalam bahasa Sanskerta. Beberapa di antaranya adalah Osmond de Beauvoir Priaulx yang menyebut bahwa nama "Zarmanochegas" berasal dari kata Çramanakarja ("pengajar Śramaṇa"). Sedangkan Charles Elliot berpendapat bahwa nama "Zarmanochegas" berasal dari kata śramaṇa dan açarya ("sang guru Śramaṇa").
Sejumlah tokoh filsuf Yunani juga diketahui terinspirasi dari pemikiran-pemikiran Śramaṇa, terutama gaya hidup gymnosofis yang jelas-jelas dipengaruhi oleh model pertapaan pengembaraan tanpa sekte yang biasa dilakukan oleh para pertapa Śramaṇa pemula. Beberapa di antaranya adalah Pyrrho (w. circa 270 SM), seorang filsuf Yunani klasik yang mendirikan sekolah Pyrrhonisme. Sebagian besar pengajaran filsafat Pyrrhonisme secara jelas dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Sang Buddha. Pengaruh Śramaṇa yang sebagian besar dari Buddhisme di dalam gagasan Pyrrho sangat mudah dipahami, karena Pyrrho bersama Anaxarchus ikut serta dalam ekspedisi Alexander Agung ke India barat pada tahun 327-325 SM, yang merupakan titik awal dimulainya periode kebudayaan Greco-Buddhisme seperti yang telah dijelaskan di awal.
BACA JUGA :
Akhir Dari Gerakan Pertapaan Śramaṇa

Gerakan pertapaan Śramaṇa mulai jarang ditemui pada abad ke-8 sampai 12. Beberapa faktor penyebab berakhirnya gerakan pertapaan ini di antaranya adalah telah matangnya sejumlah doktrin dalam Śramaṇa sehingga tidak lagi menjalani perilaku hidup selibat. Sejumlah doktrin tsb kita ketahui sekarang sebagai agama-agama besar dunia, seperti Buddhisme dan Jainisme, serta Hinduisme heterodoks. Kematangan tsb dicapai karena praktik Śramaṇa seringkali melibatkan dialektika antar pertapa, sehingga sangat rentan terjadi sinkretisme. Dan pada hakikatnya, sekolah-sekolah/mazhab-mazhab yang berdiri dari kalangan Śramaṇa adalah sebuah upaya lanjutan untuk membakukan (kanonisasi) ajaran-ajaran yang diajarkan pendirinya. Bahkan, sebuah "universitas kuno" Buddhis saat itu telah berdiri untuk mewadahi intelektualisme ajaran-ajaran Sang Buddha, yaitu Mahavihara Nalanda yang menjadi salah satu universitas kuno terbesar saat itu sejak abad ke-5 sampai abad ke-13 (TS juga pernah membuat thread khusus: Selamat Datang di Universitas Nalanda yang Legendaris. Karena sudah mulai banyak sutta Buddha yang ditulis dan diterjemahkan, begitu juga dengan tradisi dialektika di kalangan Buddhisme, dan terutama sekali karena telah berkembangnya ilmu pengetahuan (sains), gerakan pertapaan Śramaṇa menjadi kurang diminati, karena tidak efisien dan tidak efektif. Ketika 'Abbasiyyah berkuasa, penyebarluasan sains Greco-Buddhisme juga mencapai dunia Islam, dan di saat itu pula terjadi pertukaran budaya dan sains.
Namun demikian, bukan berarti pertapaan pengembaraan sudah tidak ada lagi. Sisa-sisa tradisi Śramaṇa masih dapat dirasakan hingga hari ini untuk setidaknya di India. Sejumlah tokoh spiritual India modern juga memulai sekte/mazhabnya dari pengembaraan dan pertapaan. Bahkan, sekte-sekte dan/atau agama-agama "New Ages" ini menempati kedudukan mayoritas penganut umat beragama di India. Terdapat kira-kira 77,49% penganut agama "New Ages" di India hari ini. Beberapa tokoh spiritual pendiri agama-agama tsb cukup terkenal, seperti Mastana Balochistani yang mendirikan kultus Dera Sacha Sauda (DSS), Osho (1931-1990) yang mendirikan gerakan Rajneesh, Sadhguru yang mendirikan Isha Foundation, dan masih banyak lagi. Beberapa tokoh spiritual tsb ada yang tidak mendirikan sekte, namun penerusnya mendirikan sekte kultus baginya, contohnya adalah Shirdi Sai Baba (w. 1918) yang kemudian penerusnya, Sathya Sai Baba (1926-2011) mendirikan Sri Sathya Sai International Organization (SSSIO). Tentu saja terdapat perbedaan sangat menonjol antara gerakan Śramaṇa dengan tokoh-tokoh spiritual "New Ages", dimana perbedaan paling menonjol adalah dari corak pemikirannya. Jika pada gerakan Śramaṇa, para pertapa ini umumnya tidak hanya menelurkan gagasan mistik, namun yang lebih penting adalah sebuah epistem. Kita dapat melihat betapa sebagian besar epistem dari gerakan Śramaṇa masih dianut sampai hari ini, seperti misalnya obyektifisme, empirisme, fatalisme, determinisme, anti-determinisme, skeptisisme, sinisme, panteisme, dsbnya, dan barangkali inilah pengaruh Śramaṇa yang masih bisa dirasakan secara luas sampai hari ini. Hal ini berbeda dengan tokoh-tokoh spiritual "New Ages" yang umumnya berkutat kepada persoalan mistik dan ritus mistika belaka. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan pertapaan Śramaṇa telah membawa pengaruh besar dalam perkembangan peradaban manusia.
Meskipun gerakan pertapaan Śramaṇa praktis sudah tidak ada sejak abad ke-13, namun pengaruhnya masih sangat kuat di India, dan bahkan ke berbagai agama-agama dunia. Sebagian besar agama besar dunia juga memiliki kisah-kisah pengembaraan para tokoh sucinya yang kurang lebih mirip dengan Śramaṇa. Tradisi mengembara untuk hidup selibat ini telah mewarnai khazanah kebudayaan umat manusia.